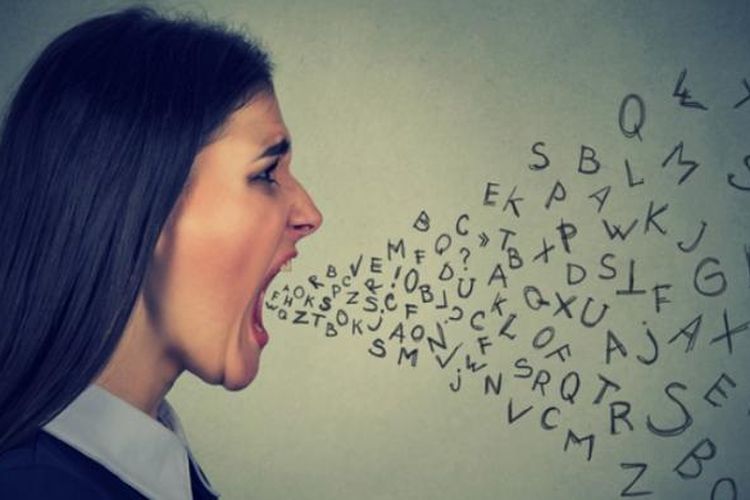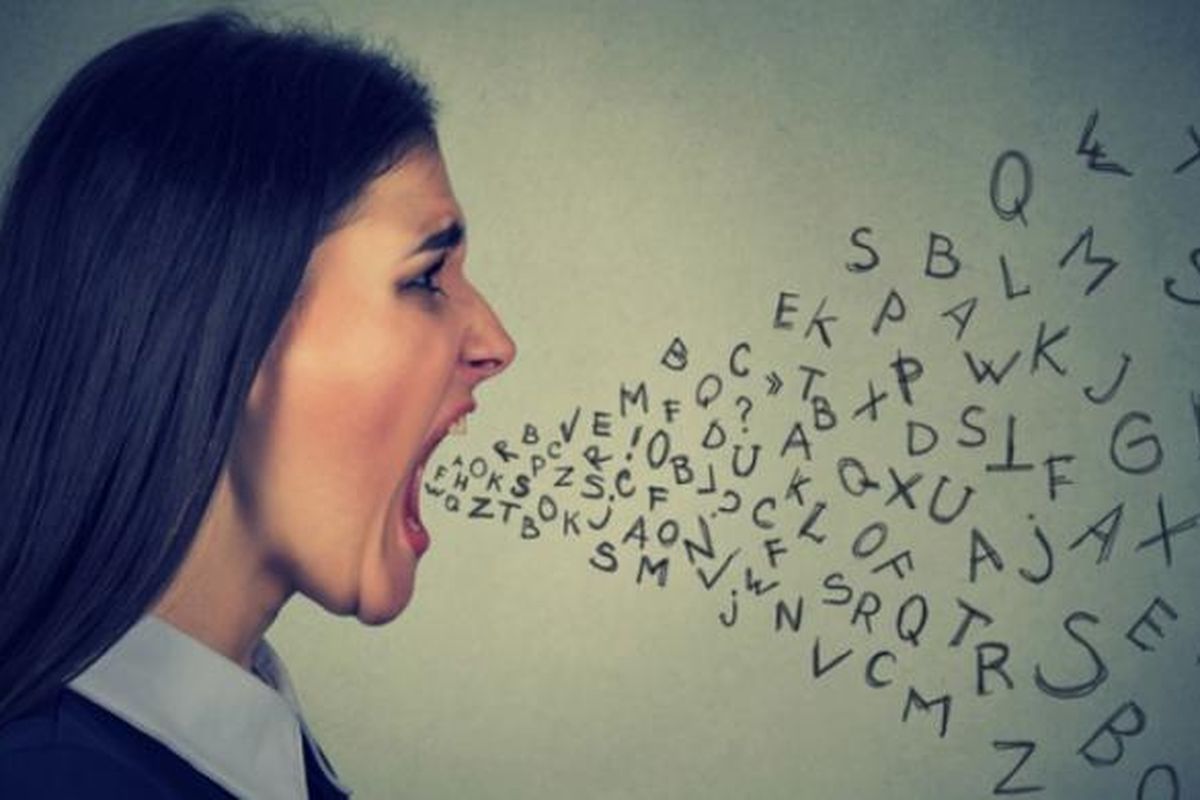
Kebencian akibat pola pikir kronis amat individual. Namun, saat individu-individu yang membenci mengelompok, skema berpikir kronis berlaku pada kelompok. Jadi, identitas kebencian mereka mengental dan membuat mereka terpolarisasi dengan kelompok lain.
Kehadiran pimpinan kelompok mengukuhkan identitas mereka. Jika pesan kebencian dari pimpinan kelompok disampaikan berulang-ulang, realitas yang dikonstruksikan pimpinan kelompok jadi realitas kelompok.
"Akibatnya, mereka tak kritis dengan kelompoknya. Kelompoknya paling benar dan kelompok lain salah," kata Rahmat.
Taufiq menyebutkan, kebencian yang berubah dari ekspresi personal jadi ekspresi kelompok bisa memicu konflik horizontal. Masalahnya, kebencian massal mudah menyebar karena manusia Indonesia yang paternalistik suka mengelompok. Dampaknya, mereka tak percaya diri dengan penilaian diri dan memilih mengikuti pandangan kelompoknya.
Namun, kebencian yang disebar itu belum tentu memunculkan kebencian serupa pada orang lain. Penerimaan individu pada ujaran itu menentukan mereka ikut membenci atau tidak. "Penyebaran kebencian hanya menguatkan pandangan kelompok, tak otomatis memengaruhi pandangan orang atau kelompok umum," ucap Rahmat.
Namun, persepsi itu dipengaruhi kesukaan seseorang pada figur penyebar kebencian. Kesukaan pada penyebar kebencian menjadikan seseorang setuju kebencian yang disebar. Sebaliknya, ujaran positif dari orang yang dibenci bisa melahirkan kebencian.
"Pembenci memandang seseorang bukan atas apa yang dibicarakannya, tetapi siapa yang membicarakannya," ujarnya.
Pembatasan
Meski ujaran kebencian berdampak nyata di masyarakat, pengaturannya di sejumlah negara menimbulkan pro dan kontra, termasuk di Amerika Serikat dan Indonesia. Pengaturan ujaran kebencian dikhawatirkan memengaruhi kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.
Rahmat menilai, sebagai ekspresi personal, ujaran kebencian tak perlu dikontrol negara karena khawatir akan membatasi kebebasan berpendapat. Dalam jangka pendek, penyebaran pandangan negatif memunculkan ketidaknyamanan. Namun, dalam jangka panjang, belum tentu bisa memengaruhi orang lain.
"Prinsipnya, kebebasan berpendapat tak boleh dilanggar. Etika berkomunikasi harus dijaga dan negara tak perlu jadi polisi moral masyarakat," katanya.
Namun, banyak pihak juga mengingatkan, kebebasan berbicara itu tetap bisa dibatasi jika melanggar hak-hak orang lain atau menimbulkan dampak bagi bangsa dan negara.
Berdasar neurosains, Taufiq setuju jika kebebasan berbicara, khususnya yang menyangkut penyebaran kebencian, harus dibatasi. Sifat dasar manusia selalu ingin melampiaskan segalanya. Kondisi itu akan menghilangkan kendali diri hingga bertindak membabi buta, tak bisa menenggang rasa, bahkan jadi agresif.
"Karena kebencian merusak otak, kebencian tidak boleh terjadi masif. Kebencian itu menular dan berlaku bak bola salju sehingga bisa menimbulkan malapetaka," ucapnya.
Di sisi lain, pembeda antara ujaran kebencian dan kebebasan berpendapat adalah motifnya. Ujaran kebencian selalu dilandasi rasa benci serta semangat permusuhan dan merupakan perilaku kompulsif yang terjadi berulang-ulang. Kelompok yang disasar pembenci selalu salah, tidak pernah benar.
Sementara kebebasan berpendapat merupakan sikap kritis pada kelompok tertentu secara obyektif. Benar dan salah adalah dua hal yang bisa melekat pada siapa pun. "Meski tampilan lahiriahnya sama, kebebasan berpendapat lebih positif," ujarnya. (M ZAID WAHYUDI)
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Januari 2017, di halaman 5 dengan judul "Tebar Kebencian, Tumpulkan Pikiran".