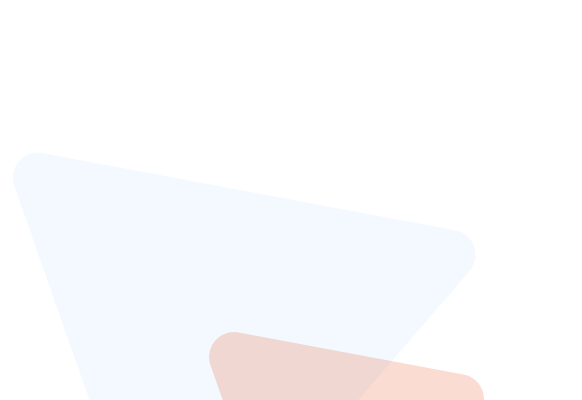Dosa dan Agama
KOMPAS.com — Agama mestinya mendamaikan. Akan tetapi, agama yang menekankan pada penilaian-penilaian buruk memantapkan citra diri negatif. Agama yang sekadar dipahami dan digunakan sebagai bentuk penghukuman (pada diri sendiri dan pihak lain) hanya akan menghancurkan.
Seorang gadis muda mengirim surat ini: ”Mama baik, tiap pagi masak untukku, kerja cari uang untuk aku. Tapi juga sangat mudah marah. Waktu kecil aku terpaksa tidur siang karena takut dihukum. Aku tidak berani membayangkan rotan kemoceng yang dipegang mama tiap menemani aku mengerjakan PR atau belajar. Aku harus sempurna dan bisa menjawab semua pertanyaan. Aku sebenarnya lambat berpikir dan sensitif dengan bentakan.
Ketika mama membentak, aku langsung menangis. Mama akan semakin marah karena aku terlalu cengeng. Di masa remaja aku malu dengan penampilanku sendiri. Aku sering berbeda pendapat dengan mama, dan itu sering berakhir dengan teriak-teriakan dari mama. Aku kasihan pada mamaku, yang sangat mengabdi pada papa tapi diperlakukan kasar dan dihina-hina oleh papa. Aku berjanji dalam hatiku, suatu saat ketika aku menikah, aku ingin mengajak mama tinggal denganku. Tapi tiap berbeda pendapat mama malah bilang: ”Tidak tahu terima kasih! Aku tidak akan mau tinggal dengan kamu, tidak ngerti agama, anak durhaka...!’
Aku sungguh berdosa. Berdosa. Berdosa. Berdosa. Jahat. Jahat. Durhaka. Aku memarahi diriku yang berbeda pendapat dengan mama dan bodoh. Aku malu, aku tak berdaya. Aku ingat teriakan-teriakannya: ’Bodoh! Merasa pintar, padahal belum tahu apa-apa! Sialan! Anjing! Anak setan! Aku pastikan, nanti kalau punya suami, dia pasti memukuli kamu!’. Mama bilang, meski orang-orang selalu memuji aku tapi mama tidak pernah bangga malah malu karena tahu siapa aku sebenarnya yang tidak ngerti agama.
Aku ingin pergi. Tapi agama bilang aku tidak boleh durhaka, harus menjaga orangtua. Aku bilang pada kakakku, aku mau kos. Ia langsung teriak marah dan mengancamku, ”Kalau sampai terjadi apa-apa pada mama, semua itu adalah salah kamu!!!! Ngerti kamu?!!” Brak!!! Pintu pun dibanting.
Aku urung pergi. Tak mampu membayangkan perasaan berdosa membiarkan mama sendiri bertahan hidup dengan suami yang tidak pernah memberi uang sepeser pun sejak pernikahan mereka. Aku berharap agama membantuku menjadi lebih dewasa menerima kenyataan hidup, merasa lebih tenteram dan damai. Tapi hingga sekarang bahkan aku masih membenci diri sendiri, belum dapat berdamai dengan diri sendiri.”
Kehidupan pribadi
Apabila pendidikan dalam rumah diisi oleh penghinaan dan penilaian-penilaian negatif, tuntutan-tuntutan yang sifatnya satu arah, dan tidak timbal balik, maka agama malah mungkin menghancurkan. Bedakan dengan situasi yang lebih positif ketika orangtua memberi contoh konkret, menyampaikan pujian ketika anak berlaku baik, menegur dalam bahasa positif, tidak berstandar ganda (hanya menuntut pihak lain, tetapi tidak menerapkan aturan bagi diri sendiri).
Dalam kehidupan pribadi dan hubungan interpersonal, situasi sudah sangat kompleks. Manusia memiliki dorongan-dorongan pertumbuhannya sendiri: ingin memiliki citra diri positif, ingin berkembang sesuai dengan fitrah masing-masing yang unik, dan terdorong untuk melindungi diri ketika diperlakukan buruk oleh orang lain.
Di sisi lain, kita juga ingin dinilai positif oleh orang lain, lalu mencoba semaksimal mungkin menyesuaikan diri dengan penilaian dan harapan orang lain. Akibatnya, sering terjadi konflik batin yang kadang menetap dalam jangka panjang secara sangat menyakitkan. Dalam hubungan orangtua-anak, ilustrasi di atas dapat memberi gambaran. Citra diri buruk dan situasi menyakitkan juga dapat terjadi dalam hubungan suami-istri dan dalam hubungan-hubungan interpersonal lain.
Kehidupan sosial
Dalam kehidupan sosial, situasinya jauh lebih kompleks lagi. Apabila kita kuat dikungkung oleh keyakinan dan aturan-aturan normatif mengenai bagaimana menjalankan ritual agama dan berperilaku yang "benar" dan "seharusnya", kita mungkin menghayati "dorongan besar" untuk memastikan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain untuk patuh pada aturan normatif tersebut.
Kita ingin memastikan bukan hanya kita yang menjalankan aturan tersebut, melainkan juga orang lain. Kita akan menggunakan standar moralitas kita untuk mengukur orang lain, untuk mengotak-ngotakkan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, bahkan mungkin memaksa pihak lain untuk berperilaku sesuai pandangan kita mengenai kebenaran.
Demikianlah kemudian dapat terjadi diskriminasi dan kekerasan pada pihak-pihak lain yang dinilai buruk atas nama keyakinan atau ajaran agama. Situasi lebih runyam lagi apabila keyakinan agama dipolitisasi dan dieksploitasi untuk kepentingan di luar agama (misal: keuntungan ekonomi menjual produk X, memenangi pemilihan ketua Y di mana yang dianggap boleh jadi pemimpin hanya laki-laki, atau hanya orang dari agama Y).
Persoalan global
Dunia masa kini penuh dengan persoalan; makin sesak dan sempit untuk dihuni, makin membutuhkan keberanian dan "sikap tega" untuk berkompetisi dan mengalahkan pihak lain. Dalam situasi demikian, ketakutan dan kecurigaan antarkelompok dapat menjadi makin tajam. Alhasil, diskriminasi dan kekerasan juga makin mudah terjadi.
Dalam salah satu sesi paralel dalam konferensi Hukum dan Penghukuman yang berlangsung di Universitas Indonesia, Depok, 28 November-1 Desember 2010, dipaparkan oleh Prof Dr Marilyn Porter dari Kanada bahwa di Kanada sesungguhnya juga terjadi friksi-friksi antarkelompok. Apabila di Indonesia kelompok minoritas (dalam arti luas) seolah dipaksa untuk menjadi "sama" dan tidak boleh berbeda, demikian pulalah di Quebec, salah satu provinsi di Kanada, yang cenderung homogen dan diisi warga Kanada berbahasa Perancis. Dan yang lebih rentan tampaknya sama, yakni perempuan, yang perilaku dan cara berbusananya diatur-atur.
Di Indonesia, perempuan Muslim yang tidak menutup kepala mungkin dikomentari "kurang beragama". Di Quebec, perempuan Muslim yang ingin menutup kepala mungkin harus siap didiskriminasi. Jadi, persoalannya bukan pada agama atau aliran keyakinan X, Y, dan Z, melainkan pada bagaimana manusia memaknainya. Apakah agama menjadi sekadar ideologi untuk dieksploitasi bagi kepentingan sendiri, ataukah menjadi spiritualitas yang sungguh memerdekakan, menghidupkan, dan mendamaikan?
KRISTI POERWANDARI psikolog