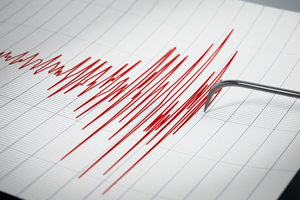DUA kasus terbaru yang muncul di Indonesia membuka luka yang tak bisa dibungkam dengan alasan prosedur atau nama baik institusi.
Dua kasus terbaru, yakni dugaan pelecehan oleh dokter kandungan di Garut dan pemerkosaan oleh dokter residen di RSHS Bandung.
Keduanya memiliki pola sama, yaitu tindakan tidak senonoh yang terjadi dalam ruang tertutup, di balut kewenangan medis, dan berlindung di balik diamnya desain ruang dan sistem pelaporan.
Namun, apa yang luput dibicarakan publik, bahkan regulator? Arsitektur ruang, baik ruang pemeriksaan, ruang tindakan, bahkan ruang tunggu berperan besar dalam memperkuat relasi yang timpang antara tenaga medis dan pasien.
Di ruang inilah, tubuh manusia tak hanya diperiksa, tetapi juga berpotensi diobjektifikasi dan dilanggar.
Baca juga: Penangguhan PPDS Anestesi RS Hasan Sadikin dan Tanggung Jawab Sistemik
Ruang medis dan ilusi netralitas
Ruang medis di Indonesia masih dianggap netral, steril, bahkan suci. Namun, dalam realitas sosial, ruang itu adalah arena dominasi, bukan semata-mata karena keahlian dokter, tetapi karena desain yang membuat pasien kehilangan kontrol.
Pasien yang berbaring dalam posisi litotomi, tak bisa melihat tangan dokter. Tirai yang menutup wajah pasien dari alat, layar, dan bahkan pendamping.
Pintu yang tertutup rapat tanpa jendela. Tidak ada alarm. Tidak ada jeda untuk verbal consent di setiap tahap tindakan.
Ini bukan ruang penyembuhan. Ini adalah ruang kosong dari pertanggungjawaban.
UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjamin hak pasien atas privasi, persetujuan tindakan, dan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi.
SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit) mengatur bahwa rumah sakit harus menghormati kebutuhan privasi pasien dalam pemeriksaan.
Namun, tidak satu pun regulasi bicara tentang desain ruang sebagai alat pencegah kekerasan. Tidak ada kewajiban ruang untuk memiliki buffer zone, cermin reflektif, tombol panik, atau SOP verbal dalam USG transvaginal.
Regulasi kita menganggap etik dan moral cukup mengawal ruang. Padahal justru dalam diamnya ruang, predator bersembunyi.
Ketika teori kriminologi berbicara tentang kontrol sosial sebagai benteng terakhir, sistem hukum Indonesia justru memercayakan perlindungan korban kepada keheningan prosedur administratif.
Kita belum memiliki regulasi eksplisit yang mempersoalkan bagaimana ruang dapat memperkuat atau melumpuhkan mekanisme etik. Ini adalah lubang hitam legislasi.