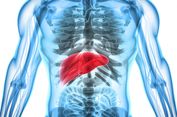Oleh M Zaid Wahyudi
Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Hanya karena satu masalah yang dianggap tak patut atau berbeda dengan pandangan masyarakat, sirna sudah semua kebaikan yang dimiliki seseorang.
Sosok yang sebelumnya dimuliakan tiba-tiba menjadi pribadi yang dianggap hina. Ditinggalkan raganya, diabaikan keberadaannya, bahkan direndahkan harkatnya.
Hal itu dialami sejumlah tokoh yang dikenal sebagai figur yang mempromosikan nilai-nilai moral dan kemuliaan jiwa di masyarakat. Mudahnya masyarakat mengagumi dan mengagungkannya, semudah itu pula mereka meninggalkannya.
Sebagaimana diberitakan sejumlah media massa, kasus terbaru ialah masalah yang dihadapi seorang motivator terkemuka. Kasus serupa pernah dialami seorang penceramah agama kondang saat berpoligami. Demikian pula kondisi sejumlah orang yang mengaku sebagai guru spiritual.
Masyarakat Indonesia ialah masyarakat emotif. Cara berpikirnya amat didominasi perasaan. Mereka cenderung enggan menalar atau mengolah informasi memakai akal karena proses itu rumit dan melelahkan bagi otak. Mereka lebih suka menerima sesuatu yang menyenangkan saja bagi dirinya.
"Akibatnya, mereka cepat menilai dan membuat kesimpulan. Pengambilan keputusan tak didasari penilaian lengkap dan valid," kata Kepala Pusat Studi Otak dan Perilaku Sosial Universitas Sam Ratulangi, Manado, Taufiq Pasiak, Kamis (15/9).
Dominannya emosi membuat bagian otak yang jadi pusat pengatur emosi atau limbik membajak korteks prefronal, bagian otak pengendali proses berpikir rasional.
Cara berpikir itu membuat penilaian atas moral didasari atas apakah penilaian itu memuaskan atau tidak bagi dirinya, bukan soal benar atau salah. Paparan media sosial yang amat besar kian membuat orang malas mengklarifikasi informasi yang beredar. Padahal, pengecekan informasi itu bisa dilakukan dari telepon seluler yang sama, yang digunakan untuk menjelajahi media sosial.
Psikolog sosial yang khusus meneliti relasi sosial dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Avin Fadilla Helmi, menjelaskan, masyarakat Indonesia, sama dengan warga Asia lain, suka membangun relasi. Relasi jadi kebutuhan sehingga mereka tak suka berbeda pendapat, apalagi berkonflik. "Mereka selalu menginginkan kondisi harmonis," katanya.
Jika dalam berelasi itu, termasuk dengan sosok yang dikagumi, muncul masalah, mereka akan menjauh, melepaskan ikatan relasinya. Namun, dalam banyak kasus, pelepasan ikatan itu hanya sementara. Meski sempat ditinggalkan, sosok idola itu bisa kembali menjadi panutan masyarakat meski penerimaannya tak akan bisa sama seperti sebelumnya dan butuh waktu.
Namun, agar bisa diterima kembali, sosok itu harus melakukan introspeksi dan transformasi diri. "Transformasi diri itu ditangkap masyarakat dan warga bisa memaafkan," ujarnya.
Taufiq menambahkan, mudahnya masyarakat memaafkan dan melupakan kesalahan yang dibuat sosok sebelumnya adalah buah dari cepatnya mereka menilai dan mengambil putusan. Pola penilaian didasari perasaan bersifat jangka pendek, mencuat sesaat, dan cepat dilupakan.
Tak belajar
Cara berpikir emotif itu pula yang membuat kelompok pendukung (lover) dan penentang (hater) calon presiden pada Pemilu 2014 tetap ada meski pemilu telah lewat lebih dari dua tahun. Setiap pendukung membela mati-matian calon yang pernah didukung tanpa melihat apa yang dilakukannya benar atau salah.
Meski terjadi berulang, masyarakat tak cukup mengambil pelajaran dari setiap masalah yang terjadi. Kebiasaan berpikir memakai rasa itu disuburkan dengan sistem pendidikan di sekolah yang tak mengajarkan berpikir kritis karena lebih mengutamakan hapalan.
Pola pikir emotif itu juga didukung karakter masyarakat yang memahami agama bukan dengan cara berpikir, tetapi menerima begitu saja. "Itu adalah ciri masyarakat emotif, menerima apa adanya, dan enggan berpikir. Akibatnya, masyarakat amat sensitif dengan hal-hal berbau agama," tutur Taufiq.
Masyarakat emotif juga amat dipengaruhi simbol. Dalam beragama, mereka cenderung ritualistik dan memaknai agama secara hitam-putih. Meski manusia Indonesia dinilai munafik, permisif dan hipokrit, hal-hal berbau religius masih jadi perhatian. Mereka sensitif dengan hal-hal yang dianggap baik, termasuk agama, tetapi tak sensitif dengan sesuatu yang buruk.
Mereka juga menjadikan agama sebagai simbol belaka, tak termanifestasikan dalam perilaku. Karena itu, meski mereka memiliki ritual bagus, agama tak jadi bagian dalam pengambilan keputusan.
Walau mereka menangis saat ikut doa bersama atau mengikuti pelatihan motivasi, hanya sebagian nilai agama yang membekas setelah acara selesai.
"Kondisi itu membuat mereka yang dinilai religius atau menyosokkan diri religius akan dianggap melakukan pelanggaran lebih berat dibandingkan mereka yang tak menonjolkan sisi religiusnya meski bobot kesalahannya sama," ujarnya. Itulah yang membuat penyanyi yang pernah terlibat kasus pornografi bisa diterima, bahkan kembali disukai warga.
Kemampuan bernalar
Avin menambahkan, dengan kemampuan menalar rendah, masyarakat menilai seseorang berdasar informasi permukaan atau citra visualnya saja. "Nalar yang terbatas membuat kita mudah tertipu citra," katanya.
Selain itu, landasan moral masyarakat dipengaruhi norma sosial. Media sosial kian mendukung norma sosial itu. Meski orangtua menanamkan integritas moral sebaik apa pun, saat dihadapkan norma sosial yang tak mendukung integritas moral itu, mayoritas warga memilih mengikuti norma sosial masyarakat.
"Meski orangtua mengajarkan kejujuran, karena sebagian birokrasi menciptakan ketidakjujuran tak apa-apa, lebih banyak orang memilih tak jujur," ucapnya.
Mengikuti pola lingkungan tak jadi soal jika berpengaruh positif. Di Indonesia, tak semua lingkungan sosial kondusif membuat orang berbuat baik atau menjaga moral.
Cara berpikir yang mengedepankan rasa hingga mudah menilai, membuat masyarakat mudah diprovokasi dan dibenturkan. Warga cenderung melihat perbedaan, bukan persamaan. "Jika tak dibenahi, bangsa Indonesia rentan terpecah belah oleh hal sepele," kata Taufiq.
Pada beberapa suku bangsa di Indonesia, pola pikir mengutamakan rasa itu amat kuat. Belum lagi kekayaan alam melimpah membuat tak perlu usaha besar demi mendapat sesuatu. Penjajahan Belanda selama 350 tahun yang tak membangun pendidikan umum, hanya bagi elite tertentu, memperparah kondisi itu.
Hal itu membuat bangsa Indonesia tak terbiasa mengolah pikiran, apalagi berpikir bebas. Cara pikir pendek juga membuat bangsa Indonesia sulit berpikir kritis dan kreatif sehingga kurang mampu berinovasi.
Meski demikian, kondisi itu bisa diubah, seperti yang dilakukan negara-negara Asia lain yang pola relasinya sama. "Pendidikan ialah teknologi yang bisa mengubah manusia berpikir lebih baik," ujar Taufiq.
Pendidikan yang mengajarkan daya pikir berdasar olah pikir akan membuat manusia Indonesia bisa mengendalikan emosi sehingga bisa mengambil tindakan berdasarkan pemikiran matang.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 9 Oktober 2016, di halaman 6 dengan judul "Saat Menilai dengan Emosi".
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.